Oleh: Fakhri Afif
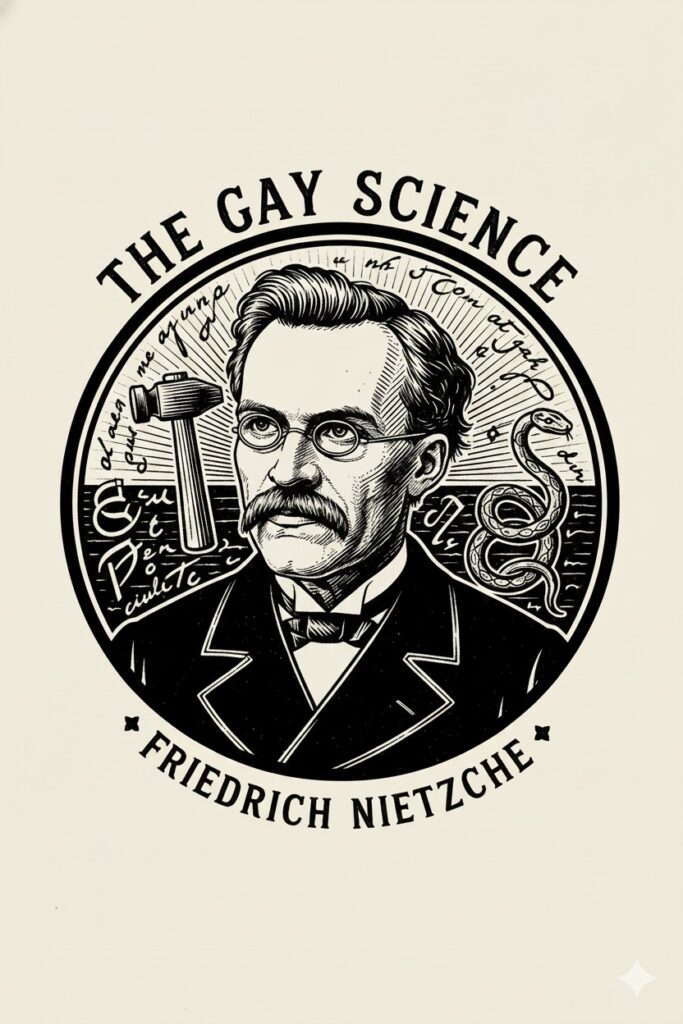
Dari “Kebenaran Diri” ke Kecurigaan Nietzsche
Di sekitar kita, bahasa tentang “diri” dan keaslian sudah hampir menjadi mantra resmi yang sakti zaman ini. Kita dinasihati untuk menemukan jati diri yang autentik, “jujur pada diri sendiri”, “menjadi diri sendiri”, seolah-olah persoalan utama kehidupan modern hanya terbatas pada apakah kita sudah cukup setia kepada “siapa kita sebenarnya”. Berbagai buku self-help, khotbah yang dikemas kekinian, konten motivasi di TikTok dan YouTube, hingga obrolan di kafe sering bertemu pada satu gagasan yang sama, bahwa di dalam diri setiap orang tersembunyi sebuah inti batin—“aku yang sejati”—yang tugas kita adalah menggali, membersihkan, lalu mewujudkannya. Krisis, rasa bersalah, atau kelelahan eksistensial dalam pemahaman semacam ini pun dibaca secara reduksionistik sebagai tanda bahwa kita “menjauh dari diri sendiri”. Sebagai solusinya, kita diajak untuk pulang ke pusat batin yang dianggap murni itu.
Di balik bahasa yang terdengar lembut ini sebetulnya tersembunyi dua asumsi besar yang problematik. Pertama, bahwa ada “diri” yang relatif stabil: identitas batin yang tetap sama melintasi situasi dan perubahan. Kedua, bahwa autentisitas berarti kembali ke inti tersebut—sebuah gerak mundur: menyingkirkan topeng sosial, ekspektasi, luka masa kecil, hingga tersisa sesuatu yang “sejak awal” sudah eksis. Kita membayangkan bahwa di belakang sejarah, bahasa, dan relasi, ada satu titik bening yang berdiri sendiri. Dalam konteks ini, pengembangan diri mengemban tugas dalam membawa kita pulang ke titik itu. Gagasan ini memang terasa menenangkan, tapi di situlah problem filosofis bermula: sejauh mana “inti diri” itu benar-benar real atau nyata, dan sejauh mana ia hanya merupakan konstruksi dari cara tertentu memahami manusia?
Pada titik inilah Nietzsche datang sebagai tamu pengganggu yang tidak diundang dalam pesta keautentikan modern. Ia tidak menawarkan jurus baru untuk “lebih efektif menjadi diri sendiri”, melainkan mengguncang kepercayaan konvensional mayoritas manusia pada keberadaan “diri” itu sendiri. Kalimatnya yang terkenal—“tidak ada fakta, hanya tafsiran-tafsiran”—bukan sekadar provokasi tentang pengetahuan, tetapi juga pukulan telak bagi cara kita memahami subjek. Bagi Nietzsche, apa yang kita anggap “fakta batin” tentang diri—perasaan bersalah, keyakinan “aku adalah orang seperti ini”, bahkan pengalaman “aku sedang berpikir”—selalu sudah merupakan produk penafsiran. Lebih jauh lagi, ia bahkan menuduh bahwa “subjek” sering kali tidak lebih dari sekadar fiksi gramatikal: karena tata bahasa mengajarkan bahwa di balik setiap perbuatan (deed) harus ada pelaku (doer), kita lalu menganggap di balik setiap “berpikir”, “menghendaki”, “memilih”, pasti ada satu “aku” yang stabil. Padahal, boleh jadi yang sungguh ada hanyalah rangkaian dorongan, afek, dan proses tubuh yang kemudian kita rangkum dalam kata kecil: “aku”.
Dengan cara ini, “aku” tidak lagi tampil sebagai inti yang kokoh, melainkan sebagai efek tafsir: kristalisasi sementara dari konflik dan negosiasi berbagai dorongan yang saling berebut ruang. Ketika satu konfigurasi dorongan dominan, ia menyusun narasi tentang siapa saya; narasi itu lantas dikukuhkan oleh bahasa, tradisi, dan respons sosial. Saat konfigurasi lain menang, cerita tentang diri pun mengalami pergeseran. Kesan kontinuitas—bahwa “aku yang dulu” dan “aku yang sekarang” adalah orang yang sama—lebih mirip hasil editing naratif daripada pantulan murni suatu substansi batin. Dengan berani, Nietzsche mengajak kita untuk jujur agar berhenti memperlakukan “diri” sebagai sesuatu yang berdiri di belakang tafsir, dan mulai melihat fakta bahwa diri justru lahir di dalam tafsir itu sendiri.
Jika demikian, apa yang tersisa dari obsesi kita tentang “diri autentik”? Jika yang kita sebut autentisitas juga merupakan hasil penafsiran—kemenangan satu cara memandang diri atas cara-cara lain. Di sini, pertanyaannya bergeser secara drastis. Bukan lagi, “Bagaimana aku setia pada inti batinku?” melainkan, “Tafsir macam apa yang bekerja ketika aku menyebut sesuatu sebagai ‘inti batinku’?” Bukan lagi, “Apakah aku jujur pada diriku?”, tetapi, “Dari sudut pandang siapa ‘kejujuran’ itu didefinisikan, dan dorongan apa yang diuntungkan olehnya?” Pada titik ini, “menjadi diri” kemudian tampil sebagai proses hermeneutik: pergulatan di antara berbagai cara menafsir diri, dunia, dan hubungan kita dengan keduanya.
Dalam tulisan pertama, kita telah menelusuri evolusi konsep diri: dari manusia sebagai makhluk kosmik ber-logos (Aristoteles); ke subjek berpikir (Descartes); ke subjek transendental (Kant); ke Dasein yang selalu sudah ada-di-dalam-dunia (Heidegger); lalu ke diri yang dibentuk oleh bahasa, kerja, dan konfigurasi kekuasaan (Gadamer, Derrida, Marx, Foucault). Diri bukan titik awal murni, melainkan simpul dalam jaringan kosmos, struktur, tradisi, ekonomi, dan institusi. Pada tulisan ini, saya akan mengeraskan satu nada yang sudah terdengar sejak awal, yaitu kecurigaan. Jika sebelumnya diri tampil sebagai simpul dalam jaringan makna, bersama Nietzsche kita akan menyelidiki apa yang bekerja di balik, sekaligus mendeterminasi artikulasi, simpul itu: perang tafsir, perspektif yang tidak pernah netral, dan kehendak-kehendak untuk berkuasa yang menyusup ke dalam cara kita menamai diri dan dunia. Dengan demikian, kita akan membaca subjektivitas melalui kacamata Nietzsche sebagai hermeneutika radikal: diri sebagai interpretasi dari perspektif tertentu, bertolak dari, serta dibentuk oleh, pergulatan kekuatan-kekuatan yang melampaui klaim kesadaran jernih kita.
Nietzsche di Persimpangan Hermeneutika
Menariknya, Nietzsche hampir tidak memakai istilah “hermeneutika”, tetapi cara berpikirnya bagi saya itu sangat hermeneutik. Ia membaca moralitas, agama, filsafat, sains, bahkan pengalaman diri, bukan sebagai cermin netral realitas, melainkan sebagai tafsiran yang harus dibongkar asal-usulnya dan dipertanyakan kepentingannya. Dalam hal ini, Nietzsche tidak hanya menafsir teks, tetapi menafsir bentuk-bentuk kehidupan. Dalam hermeneutika, setidaknya ada dua pertanyaan pokok. Pertama, soal jangkauan: apa yang layak menjadi objek tafsir? Kedua, soal hakikat: apa yang kita lakukan ketika menafsir—menemukan makna yang sudah ada, atau menciptakan horizon makna baru? Nietzsche bergerak di dua front ini sekaligus, dan di situlah ia bersinggungan dengan tradisi hermeneutika.
Dari segi jangkauan, Nietzsche adalah sosok yang sangat radikal. Ia memperluas wilayah tafsir dari teks ke totalitas pengalaman manusia. Dalam Beyond Good and Evil, ia menyodok klaim objektivitas sains: bahkan fisika, katanya, hanyalah interpretasi dunia, bukan pembacaan telanjang atas “fakta-fakta” yang berdiri sendiri. Cogito—“aku berpikir”—yang dipuja sebagai titik kepastian paling dasar, bagi Nietzsche, sudah mengandung paket penafsiran tentang “berpikir”, “aku”, dan hubungan keduanya. Konsep filosofis, sistem metafisika, dan “pandangan dunia” dibentuk oleh struktur bahasa—oleh tata bahasa yang memaksa kita memisah subjek-predikat-objek, oleh metafora yang membatu menjadi konsep. Moralitas modern pun bukanlah hukum alam, tapi bentuk interpretasi yang baginya sering sempit dan dangkal: ia membaca kehidupan dari sudut pandang kelemahan yang membenci kekuatan, lalu menamakan kebenciannya itu “kebaikan”. Bahkan “kehendak” atau “niat” dalam tindakan hanya ia anggap sebagai tanda dan gejala yang masih perlu ditafsir.
Artinya, sejak awal Nietzsche menempatkan subjek dan dunia dalam medan interpretasi tanpa residu “fakta mentah” di luar tafsir. Tidak ada wilayah suci—entah sains, moral, agama, atau batin—yang kebal dari hermeneutika. Hermeneutika bergeser dari teknik membaca teks menjadi cara membaca keberadaan. Dari segi hakikat penafsiran, Nietzsche memberi jawaban lain. Baginya, menafsir bukan sekadar mengungkap makna tersembunyi seperti arkeolog menyapu debu dari fosil. Melampaui itu, Nietzsche menilai bahwa menafsir adalah ekspresi perspektif. Setiap tafsir berangkat dari sudut pandang tertentu—tubuh, sejarah, posisi sosial, cara hidup spesifik—dan sekaligus merupakan ekspresi kehendak untuk berkuasa. Saat sebuah interpretasi berkata, “beginilah dunia sebenarnya”, di belakangnya selalu ada dorongan untuk menata dunia agar mendukung nilai dan kepentingan tertentu. Tidak ada fakta murni tanpa tafsir, dan tidak ada tafsir yang netral tanpa kehendak.
Di sini Nietzsche berjalan searah dengan, sekaligus membengkokkan Immanuel Kant. Kant menunjukkan bahwa pengalaman kita akan dunia tidak pernah telanjang: ia dibentuk oleh kategori-kategori a priori (ruang, waktu, kausalitas, dan seterusnya). Dunia yang kita alami adalah dunia yang sudah terformat oleh struktur metafisis subjek. Nietzsche menerima intuisi ini, tetapi menolak klaim bahwa struktur tersebut adalah tunggal dan universal. Ia berbicara tentang beragam perspektif yang masing-masing menyusun dunia dengan caranya sendiri. Kant bertanya, “apa syarat-syarat kemungkinan pengalaman?”, Nietzsche menambahkan, “perspektif macam apa yang sedang bekerja ketika dunia tampil ‘rasional’, ‘moral’, atau ‘absurd’?” Titik tekannya pun bergeser dari “bagaimana subjek memahami dunia?” ke “perspektif apa yang sedang bekerja ketika dunia dan diri dipahami seperti itu?”. Tidak heran bila Heidegger kelak dianggap meradikalkan jejak ini: ketika ia berbicara tentang Dasein sebagai in-der-welt-sein dalam horizon pengertian tertentu, ketika ia menyebut bahasa sebagai “rumah Ada”, ia sebenarnya melanjutkan intuisi cemerlang Nietzsche bahwa dunia tidak pernah hadir tanpa kerangka penafsiran historis.
Bagi Nietzsche, kenyataan bahwa pengetahuan dan pengalaman selalu ditenun oleh perspektif tidak berarti kita harus tenggelam dalam relativisme di mana semua pendapat sama saja; justru di sinilah ia merumuskan ulang makna “objektivitas”. Karena “pandangan dari luar dunia” mustahil, objektivitas bukan berarti bebas perspektif, melainkan kemampuan menguasai banyak perspektif dan mengujinya secara kreatif—seperti sosok filsuf ideal yang telah menjadi kritikus, skeptikus, sejarawan, penyair, pengembara, pemecah teka-teki, dan free spirit sehingga mampu “melihat dunia dari banyak mata” dan dari berbagai ketinggian-kedalaman. Objektivitas hermeneutik, dengan demikian, adalah kelapangan pandang (multi-perspectivality): kesediaan mengakui dan merefleksikan kepentingan sendiri, lalu menimbang bacaan kita melalui kacamata orang lain, termasuk mereka yang selama ini dibungkam. Jika segala sesuatu—sains, moral, bahkan pengalaman batin—adalah medan tafsir yang diekspresikan oleh perspektif dan kehendak tertentu, maka hal yang sama berlaku bagi cara kita mengenal diri: kejujuran terhadap diri menuntut keberanian untuk meminjam “mata” yang lain, melihat diri dari sudut pandang yang tidak nyaman—dari mereka yang kita kritik, kita anggap lemah, bahkan dari dorongan-dorongan dalam diri yang selama ini ingin kita tolak.
Nietzsche Melawan “Subjek” Modern
Dalam tradisi modern sejak Descartes dan Kant, “subjek” nyaris dipahami sebagai entitas yang sakral. Descartes menjadikannya sebagai titik tolak kepastian: ketika segala boleh diragukan, “aku yang sedang berpikir” tetap tidak tergoyahkan. Kant lalu menghaluskannya: subjek bukan “aku” psikologis, melainkan struktur metafisis-transendental yang mendahului sekaligus mempersyaratkan pengalaman; di balik pengalaman yang beragam, selalu ada “kesatuan apersepsi” dalam satu “aku berpikir”. Dalam dua versi ini, subjek tetap pusat kesatuan, stabilitas, dan legitimasi. Nietzsche memang menerima bahwa kita mengalami kontinuitas: kita merasa sebagai “orang yang sama” dari hari ke hari. Tetapi ia menolak penjelasan klasik tentang kontinuitas itu. Dalam pandangan Nietzsche, “Aku” bukan sumber tunggal tindakan, melainkan hasil dari rasionalisasi yang datang belakangan. Apa yang kita kenali sebagai pikiran, kehendak, keputusan sejatinya lahir dari pergulatan berbagai dorongan tak sadar; kesadaran datang terlambat, lalu menyusun cerita rapi seolah semua diputuskan secara jernih. “Niat murni”, kata Nietzsche, sering tidak lebih dari siaran pers setelah perang: teratur, koheren, dan selektif.
Pada titik ini, bahasa mempunyai andil besar: tata bahasa memaksa kita menaruh subjek di depan predikat. Kalau ada perbuatan, pasti ada pelaku; kalau ada “berpikir”, pasti ada “yang berpikir”. Struktur ini menggiring kita membayangkan dunia sebagai kumpulan substansi dengan sifat tetap: “jiwa” yang berpikir, “aku” yang menghendaki. Padahal mungkin yang ada hanyalah rangkaian afek, naluri, dan dorongan tanpa perlu diasalkan pada satu entitas stabil. Kita terbiasa berkata, “Aku memutuskan”, seolah satu pusat batin menguasai semua motif; Nietzsche justru melihat keputusan sebagai hasil tarik-menarik kekuatan internal dan eksternal yang tidak kita kuasai, sementara “aku” datang belakangan untuk mengklaimnya. Dengan demikian, subjek bukanlah fakta metafisis, melainkan fiksi yang berguna. Saya katakan berguna karena ia efektif dalam menstabilkan pengalaman: ia memberi rasa bahwa ada “aku yang sama” yang menanggung konsekuensi tindakan, menerima pujian dan hukuman, membuat janji dan memikul tanggung jawab. Tanpa fiksi ini, kehidupan sosial jauh lebih kacau. Tetapi kegunaan praktis tidak otomatis menjadikannya benar sebagai deskripsi hakikat manusia. Nietzsche mengajak kita membedakan antara kebutuhan praktis akan stabilitas dan klaim teoritis tentang “inti diri” yang homogen dan transparan.
Ia pun menggeser pertanyaan: bukan lagi “siapa subjek yang berpikir?”, tetapi “dorongan apa yang sedang berpikir di dalam diriku, dan atas nama apa ia mengklaim pikiran itu sebagai miliknya?”. Alih-alih mencari satu titik jernih di belakang arus pengalaman, ia menyarankan kita melihat arus itu sebagai hasil pertarungan: berbagai kehendak dan kebiasaan tafsir berusaha menyusun dunia dan diri dengan cara yang menguntungkan mereka. Dalam horizon Nietzschean, subjektivitas bukan pusat yang menerangi dunia, tetapi efek penggumpalan dorongan-dorongan yang saling berebut ruang. “Aku” bukan lampu, melainkan nama bagi pola relatif stabil dalam permainan terang-gelap itu. Mengenal diri, karenanya, bukan menyelam menuju inti batin, melainkan membaca konfigurasi kekuatan yang tengah bekerja—sebuah operasi hermeneutik yang menuntut keberanian mengakui bahwa apa yang paling kita sebut “aku” mungkin justru apa yang paling sedikit kita kuasai.
Perspectivism: Tidak Ada Fakta, Hanya Tafsir
Jika subjek bukan pusat bening melainkan penggumpalan dorongan, langkah berikutnya nyaris pasti: mengakui bahwa cara kita melihat dunia pun tidak pernah netral. Inilah yang disebut sebagai perspektivisme, jantung hermeneutik dari pikiran Nietzsche. Ketika ia mengulang, “tidak ada fakta, hanya tafsiran-tafsiran”, ia tidak mengatakan dunia sekadar ilusi yang bebas kita karang, melainkan bahwa segala pengetahuan—termasuk pengetahuan tentang diri—selalu berangkat dari sudut pandang tertentu: tubuh tertentu, posisi historis tertentu, kepentingan tertentu, cara hidup tertentu. Tidak ada “pandangan dari luar dunia” (view from nowhere); kita selalu melihat dari suatu “di sini” yang bersifat situasional.
Seperti yang telah saya ungkapkan sebelumnya, Nietzsche searah sekaligus berbelok dari Kant. Kant menyatakan: pengalaman dibentuk oleh kategori-kategori a priori—ruang, waktu, kausalitas. Dunia yang kita alami bukan dunia pada dirinya, melainkan dunia yang sudah terformat. Nietzsche menerima bahwa tidak ada akses telanjang, tetapi menolak klaim bahwa format itu tunggal, universal, niscaya. Bagi Nietzsche, terdapat banyak sistem konsep dan nilai yang masing-masing membentuk dunia dengan cara berbeda, terikat sejarah dan kultur. Konsekuensinya, pengalaman dan pengetahuan menjadi perspektival di dua tingkat. Secara biologis-eksistensial: kita makhluk ber-tubuh, terbatas secara imanen dan relasional dengan posisi dan sudut pandang. Secara historis-kultural: kita lahir ke dalam bahasa, moralitas, dan cara berpikir tertentu yang membingkai apa yang kita anggap penting dan mungkin. Perspektif tradisi asketik yang melihat tubuh sebagai sumber dosa berbeda secara radikal dari perspektif yang menghayati tubuh sebagai medan ekspresi kekuatan; mereka bukan cuma dua opini, tapi dua dunia pengalaman.
Namun, hal itu tidak berarti bahwa Nietzsche mengikuti klaik yang melihat semua jenis tafsir sebagai sama saja. Nietzsche memang menolak absolutisme di satu sisi, namun di sisi lain ia sekaligus mengkritik relativisme datar. Karena semua pemahaman adalah perspektif, kenyataan demikian bukan berarti bahwa kebenaran telah hilang; ia bergeser medan. “Benar” bukan nama bagi cermin pasif atas fakta telanjang, melainkan bagi tafsir yang—dalam suatu horizon hidup—berhasil menata pengalaman secara koheren dan kuat, tanpa menutup mata terhadap fenomena yang penting. Dari dalam hidup yang kita jalani, kita masih bisa bertanya: apakah satu tafsir memiskinkan pengalaman? Apakah ia memaksa kita memalsukan perasaan? Apakah ia melahirkan bentuk hidup yang penuh kebencian, atau yang lebih afirmatif dan kreatif?
Jika dibawa ke ranah diri, implikasinya sangat terang. Setiap “aku mengenal diriku” adalah interpretasi perspektif tertentu: moral (“aku orang baik/buruk”), psikologis (“aku introvert/overthinker”), religius (“aku hamba yang lalai/saleh”). Semua kategori ini berguna; ia memberi bahasa. Tapi Nietzsche mengingatkan secara serius: mereka bukan cermin murni, melainkan kacamata yang menyoroti sebagian dan menggelapkan sebagian. Tafsir moral bisa membuat kita peka pada kesalahan pribadi, tapi tumpul pada kekerasan struktural. Tafsir psikologis bisa membantu memahami emosi, tapi juga mengunci kita dalam label. Tafsir religius bisa mendisiplinkan, tapi sekaligus bisa mengabadikan kebencian terhadap tubuh atau terhadap mereka yang berbeda. Hermeneutika klasik berharap bergerak dari salah paham menuju pemahaman yang lebih benar. Nietzsche menggeser hermeneutical stance tersebut: bahkan yang kita sebut “benar” sudah selalu merupakan kemenangan satu perspektif atas yang lain. Perspektivisme Nietzsche tidak menghapus kebenaran, tetapi memindahkan kebenaran ke medan tafsir.
Kehendak untuk Berkuasa sebagai Mesin Hermeneutik
Apakah semua ini berarti dunia tafsir adalah kekacauan? Nietzsche justru melihat adanya “logika” di balik keragaman perspektif: Wille zur Macht (kehendak untuk berkuasa). Penting untuk saya tegaskan di sini bahwa kehendak untuk berkuasa tidak terbatas dalam, dan hanya merujuk kepada, ambisi politik, melainkan merupakan kecenderungan dasar segala yang hidup untuk memperluas, menegaskan, dan mengintensifkan dirinya: mengatasi rintangan, memperbesar daya. Apabila kita membawanya ke dalam perbincangan hermeneutika, tafsir adalah cara tertentu bagi kehidupan menegaskan diri. Setiap dorongan punya “logika tafsir” sendiri. Dorongan asketis cenderung menafsir dunia sebagai kotor dan penuh bahaya; tubuh kemudian dibaca sebagai ancaman. Lalu lahirlah tafsir yang mengagungkan penyangkalan, pengekangan, dan pengurangan hasrat. Sebaliknya, ressentiment—kebencian yang tak berani tampil terang—menafsir kekuatan sebagai jahat; lemah disebut “baik” dan “suci”, sementara kuat dicap “jahat”. Tafsir moral lantas menjadi cara membalas dendam tanpa menyentuh tubuh lawan.
Dari sini, subjek tampak sebagai konfigurasi relatif stabil dari berbagai kehendak untuk berkuasa yang bernegosiasi. Dorongan-dorongan itu berusaha menguasai bahasa dan imajinasi kita: konflik batin, rasa bersalah, ideal diri—semuanya dapat dibaca sebagai pertarungan tafsir. Suara yang kita sebut sebagai “hati nurani” pun sejatinya memiliki perjalanan sejarah yang kompleks; ia mungkin suara dorongan yang telah lama menang dan kini menyamar sebagai suara yang paling asli. Subjektivitas, dengan demikian, adalah tata panggung sementara. Pada satu momen, panggung dikuasai oleh dorongan asketis; pada momen lain, hasrat kreatif atau kebutuhan akan pengakuan mengambil alih. Pementasan yang kita sebut “aku” adalah cerita yang disusun pemenang sementara di dalam tubuh dan jiwa.
Hermeneutika diri, dalam horizon ini, berarti juga membaca dorongan yang berbicara lewat tafsir. Siapa yang diuntungkan ketika aku menyebut diriku “berdosa”—apakah itu memperdalam kepedulian, atau mengabadikan kebencian terhadap diri? Dorongan apa yang menang ketika aku merasa “tidak layak dicintai”—kejujuran pahit, atau cara menghindari risiko kedekatan? Siapa yang bersorak ketika aku menyebut diri “berprestasi” dan “berhak dihormati”—daya hidup kreatif, atau kebutuhan rapuh menindas kecemasan dengan pengakuan? Dari sini, hermeneutika Nietzschean tidak lagi bertanya, “apa makna sejati diri?”, tetapi: “dorongan mana yang sedang menang ketika kita menafsir diri dan dunia seperti ini?”
Genealogi Moral: Hermeneutika Kecurigaan atas Diri
Metode genealogis Nietzsche menunjukkan secara konkret cara kerja tafsir ini. Dalam pembacaan saya, Nietzsche tidak menempatkan genealogi sebagai sejarah lurus yang rapi, melainkan melihatnya sebagai jalan untuk melacak asal-usul nilai dan praktik melalui jalur yang berantakan: kekerasan, kebetulan, konflik. “Asal-usul” (Herkunft/Ursprung) bukan fondasi suci, tetapi hasil perebutan. Dalam On the Genealogy of Morality, Nietzsche membedakan moralitas tuan dan moralitas budak. Pada moralitas tuan, “baik” berarti kuat, berani, penuh inisiatif; “buruk” berarti lemah. Pada moralitas budak—lahir dari kelas tertindas—terjadi pembalikan yang mencengangkan: kuat disebut “jahat”, lemah disebut “baik”. Kategori “baik”–“jahat” yang kita gunakan seolah-olah abadi, ternyata merupakan hasil konflik historis. Bahkan, rasa bersalah (Schuld) terkait erat dengan hutang (Schulden) dan hukuman: mula-mula tubuh berhutang yang disakiti, lalu kekerasan diinternalisasi menjadi hati nurani yang memukul diri.
Apabila dibawa ke ranah subjektivitas, kategori “baik”, “jahat”, “bersalah”, “malu”, “tulus” membentuk cara kita mengalami diri sebagai “pendosa”, “jiwa rendah hati”, atau “warga patuh”. Subjek moral modern—yang merasa selalu diawasi, spontan mengaitkan penderitaan dengan kesalahan pribadi—adalah hasil proses pemuridan, hukuman, internalisasi rasa bersalah, dan pengawasan. Di sini garis ke Marx dan Foucault (yang kita bahas di seri pertama) tampak: Marx menyoroti relasi produksi dan kelas; Foucault mengurai teknik disiplin dan pengawasan; Nietzsche mengguncang fondasi moral yang menopang keduanya. Genealogi, dengan demikian, menunjukkan bahwa “suara hati” yang kita anggap paling asli pun punya sejarah: ia pernah dibentuk dan diarahkan oleh kekuatan-kekuatan di luar kita sebelum terdengar sebagai bisikan batin.
Subjektivitas, Makna, dan Nihilisme
Mengapa semua ini penting bagi hidup sehari-hari? Karena bagi Nietzsche, manusia tidak terutama menderita karena sakit atau bencana, melainkan karena penderitaan terasa tidak bermakna. Kita bisa menanggung hampir “setiap bagaimana” jika punya “untuk apa”. Moralitas, agama, metafisika menyediakan “kerangka tafsir” yang membuat penderitaan tertaut pada tujuan: ujian yang menghapus dosa, jalan didikan Tuhan, bagian dari kemajuan sejarah, dan sebagainya. Mereka adalah hermeneutika eksistensial: mereka menata luka dalam cerita yang dapat ditanggung. Nihilisme terjadi ketika kerangka-kerangka ini runtuh: nilai-nilai tertinggi kehilangan kredibilitas, tetapi belum lahir tafsir baru yang hidup dan mampu menggantikannya. Kita masih memakai kata “dosa”, “kemajuan”, “keadilan”, tetapi tak lagi sepenuhnya percaya. Modernitas menuntut loyalitas pada kebenaran telanjang, namun kebenaran itu sering berbunyi dingin: hidup tak diarahkan ke mana pun, alam tak peduli harapan. Subjek modern “tahu terlalu banyak, percaya terlalu sedikit”: ia terampil membongkar, tetapi kehilangan rumah eksistensial bernama makna.
Dalam situasi ini, subjektivitas mengambil bentuk sebagai medan krisis. Apa arti “berkembang” ketika tidak ada kesepakatan tentang bagaimana “hidup yang baik”? Proyek menafsir diri—self-creation, self-branding, self-styling—bisa dibaca sebagai usaha mencari kerangka makna baru. Kita bebas “menciptakan diri”, tapi kebebasan ini menyimpan beban: kita harus menulis sendiri peta makna yang dulu disediakan agama dan tradisi, sambil tetap membawa residu-residu rasa bersalah dan butuh pengakuan yang diwariskan sejarah. Diri adalah tempat di mana krisis makna zaman ini paling tajam dirasakan: antara tuntutan hidup otentik, berdaya, produktif, sadar penuh, dan runtuhnya kerangka makna tradisional. Di sana, bahaya dan kemungkinan pun berjalan bersama.
Self-Help, Moralitas Populer, dan Religiusitas di Bawah Sorot Nietzsche
Jika percakapan ini kita turunkan ke lantai keseharian, medan yang langsung tampak adalah budaya self-help dan produktivitas. Di toko buku, deretan judul mengajarkan cara menjadi “versi terbaik diri sendiri”, mengelola waktu, menghapus limiting beliefs, membangun personal branding. Di media sosial, kita dihujani konten yang menyandingkan jam bangun, jumlah buku, nominal tabungan, dan intensitas ibadah. Ungkapan seperti “jangan jadi generasi rebahan”, “maksimalkan potensimu”, “jangan mau kalah saing”, “syukuri diri, tapi jangan cepat puas” mengambang di mana-mana. Melalui kacamata Nietzschean, saya hendak menegaskan bahwa semua ini bukan kumpulan tips netral, tetapi medan tafsir. Pertanyaan pertama: perspektif siapa yang sedang berbicara? Ketika “produktivitas” dijadikan ukuran utama nilai diri, apakah ini murni kehendak hidup lebih penuh—atau juga kehendak pasar yang membutuhkan subjek-subjek yang selalu merasa kurang, selalu butuh upgrade? Ketika “optimalisasi diri” diulang sebagai mantra, itu kehendak memperluas kehidupan, atau kehendak menyesuaikan diri dengan standar sukses sempit kelas menengah urban dan logika kapitalistik? Genealogi sederhana bisa diajukan: dari mana kategori “produktif”, “berhasil”, “gagal” itu datang, dan bagaimana ia berkaitan dengan jam kerja, sistem upah, algoritma platform, dan kecemasan status sosial?
Lapisan lain di sekitar kita yang semakin menjamur adalah moralitas religius populer: narasi dosa-pahala, bahasa “hijrah”, simbol kesalehan, kategori “mantan pendosa”, “pejuang istiqamah” di kanal dakwah digital. Narasi ini memberi kerangka makna: menata masa lalu, memberi horizon baru, menyediakan bahasa untuk bertobat. Namun hermeneutika Nietzschean mengajak kita bertanya: perspektif siapa yang berbicara ketika seseorang dicap “kurang iman” hanya karena tidak mengikuti gaya kesalehan dominan? Kehendak apa yang bekerja ketika rasa bersalah diproduksi masif—sekadar dorongan hidup jujur di hadapan Tuhan, atau juga kehendak mengendalikan tubuh, ekspresi, dan menyusun hierarki antar-hamba? Label seperti “santri milenial”, “perempuan karier salihah”, “laki-laki kepala keluarga sejati” tidak netral; mereka skrip yang membawa harapan implisit tentang bagaimana orang harus merasa, berpakaian, bekerja, mencintai, dan menilai diri.
Istilah seperti “generasi rebahan”, “anak muda tidak produktif”, “kaum mager” pun perlu dibaca genealogis. Nietzsche akan bertanya: label ini merepresentasikan perspektif siapa, menguntungkan siapa, dan menindas pengalaman siapa. Dari posisi siapa rebahan otomatis berarti gagal? Siapa yang diuntungkan ketika ketimpangan struktural direduksi menjadi persoalan moral individu: “kamu malas”, “kamu kurang disiplin”, “kamu kurang beriman”? Pengalaman siapa yang dibungkam ketika kelelahan kronis, depresi, atau kejenuhan eksistensial dibaca hanya sebagai kurang motivasi dan kurang syukur, bukan sebagai gejala dunia sosial yang sakit? Kapitalisme membutuhkan subjek yang selalu merasa “belum cukup”: belum cukup cantik, sukses, saleh, up to date. Rasa “kurang” ini menjadi mesin konsumsi barang, jasa, dan konten—salah satu bentuk kehendak berkuasa yang bekerja melalui ekonomi dan media. Dalam situasi ini, budaya self-help dan religiusitas populer bisa menjadi semacam “spiritualitas pendukung sistem”: alih-alih mempertanyakan struktur kerja atau algoritma yang mendorong perbandingan tanpa henti, beban dipindahkan ke individu: benahi mindset, kuatkan iman, tambah ibadah, perkuat personal branding.
Pada titik ini, saya ingin mengeksplisitkan bahwa pendekatan Nietzschean tidak mengajak kita untuk sinis terhadap, sekaligus menolak semua nilai. Ia tidak menyuruh kita untuk menertawakan semua kesalehan atau meremehkan setiap upaya perbaikan diri. Yang ia tawarkan adalah jarak hermeneutik: sebuah kemampuan untuk sedikit mundur dari antusiasme zaman dan bertanya, “perspektif siapa yang bekerja di sini, dan kehendak apa yang sedang diuntungkan?” Dengan jarak hermeneutik semacam ini, kita bisa memilih perspektif yang tidak mematikan hidup: yang tak menjadikan rasa bersalah senjata penghancur diri, produktivitas sebagai berhala, atau kebencian terhadap tubuh dan yang berbeda sebagai ukuran kesalehan.

Catatan Penutup: Nietzsche dan Tanggung Jawab Hermeneutik atas Diri
Bertolak dari eksposisi di atas, ulasan ini dengan uraian sebelumnya memiliki benang merah yang jelas. Seri pertama menelusuri evolusi subjektivitas: dari manusia kosmik Aristotelian, subjek Cartesian, subjek transendental Kant, Dasein Heidegger, hingga diri dalam wacana bahasa, kerja, dan kuasa ala Gadamer–Derrida–Marx–Foucault. Diri tampil sebagai simpul dalam jaringan kosmos, struktur, tradisi, ekonomi, dan institusi. Sementara itu, seri kedua ini merupakan zoom-in ke sosok yang memperkeras nada kecurigaan: Nietzsche. Ia mengingatkan bahwa di balik simpul itu selalu ada perang tafsir. Subjek dibongkar sebagai fiksi berguna: bukan sebagai substansi homogen, melainkan merupakan efek penggumpalan dorongan. Subjek adalah hasil tafsir; tafsir adalah ekspresi perspektif; perspektif digerakkan kehendak berkuasa. Tidak ada “inti diri” netral di luar sejarah, bahasa, kuasa; yang ada adalah banyak cara menafsir diri—ada yang memperkaya, ada yang memiskinkan; ada yang memperkuat, ada yang melemahkan; ada yang mengafirmasi kehidupan, ada yang menanam kebencian pada diri dan lain.
Perspektivisme Nietzsche dalam penilaian saya bukanlah invitasi serampangan bahwa “anything goes”. Justru karena semua pemahaman perspektival, tugas kita bukan keluar dari perspektif (karena pada faktanya itu memang mustahil), melainkan menilai perspektif: apakah ia mengungkap atau menutupi fenomena, jujur atau memaksa kita memalsukan perasaan, melahirkan kehidupan yang kreatif dan berani atau ressentiment dan hukuman? Konsekuensinya bagi konsep diri tentu saja sangat besar. Jiwa bukan lagi sesuatu yang homogen; yang ada multiplisitas dorongan, afek, suara. Sehubungan dengan ini, subjek adalah tata panggung yang bisa dirombak; hari ini rasa bersalah dominan, esok hasrat pengakuan, lusa dorongan melampaui batas. Maka dari itu, tanggung jawab dan konsistensi tidak lagi berarti setia pada, dan membatasi diri dalam, “inti diri yang tetap”, melainkan kesiapan mengakui konflik dorongan yang membentuk kita dan memilih secara sadar perspektif mana yang ingin kita biarkan mendefinisikan diri.
Oleh karena itu, Nietzsche tidak meniadakan tanggung jawab; ia memindahkan lokasinya. Kita tidak lagi dipanggil menjaga kemurnian suatu “diri sejati” yang konon sudah utuh sejak awal, tetapi dipanggil untuk: (1) lebih jujur membaca dorongan yang berbicara melalui tafsir diri dan dunia; (2) lebih bertanggung jawab memilih narasi yang tidak mematikan hidup dan tidak mengabadikan kebencian terhadap diri dan orang lain. Karena tidak ada tafsir yang steril dari sejarah, kita tidak bisa mengubah semua nilai menjadi “sama saja”; kita justru harus berani mengakui ada nilai yang melemahkan, ada yang menguatkan; ada cara menafsir yang menghancurkan martabat, ada yang meluhurkannya. Tanggung jawab hermeneutik atas diri, pada akhirnya, berarti menanggung dua hal. Pertama, menerima bahwa kita tak akan kembali ke kenyamanan “inti diri” yang tenang dan tunggal; diri kita memang berlapis dan retak. Kedua, di tengah keretakan itu, kita perlu berusaha untuk terus merawat tafsir yang memungkinkan kehidupan—diri sendiri dan orang lain—bergerak menuju kelapangan dengan mutu yang tinggi, bukan penyempitan dan kebencian.
Boleh jadi, setelah mengikuti perjalanan diri dalam kedua tulisan ini, pertanyaan yang patut kita renungkan bukan lagi, “Siapa aku sebenarnya?”, seolah-olah ada esensi pejal yang menunggu untuk digali di sana. Pertanyaan yang lebih selaras dengan spirit Nietzschean adalah: “Perspektif siapa yang sedang berbicara ketika aku mengatakan ‘aku’?” Dari sudut pandang mana aku menilai diriku berhasil atau gagal, suci atau kotor, kuat atau lemah? Dan—ini menurut saya yang paling penting—apakah aku bersedia, pelan-pelan dan dengan segala kerentanan, kerapuhan, dan keterbatasan, merundingkan kembali perspektif itu, agar cara aku menamai diri dan orang lain tidak lagi menjadi alat penghukuman yang membeku, tetapi bagian dari upaya kecil merawat kehidupan yang lebih jujur, lebih berani, lebih kuat, lebih tangguh, lebih bermutu, dan tentu saja, lebih manusiawi.
Daftar Pustaka
Clark, M. (1990). Nietzsche on Truth and Philosophy. Cambridge University Press.
Fraser, G. (2002). Redeeming Nietzsche: On the Piety of Unbelief. Routledge.
Katsafanas, P. (2016). The Nietzschean Self. Oxford University Press.
Katsafanas, P. (2019). Hermeneutics: Nietzschean Approaches. In K. Gjesdal & M. N. Forster (Eds.), The Cambridge Companion to Hermeneutics (pp. 158–183). Cambridge University Press.
Kaufmann, W. (1974). Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist (4th ed.). Princeton University Press.
Leiter, B. (2019). Moral Psychology with Nietzsche. Oxford University Press.
Nietzsche, F. (1968). The Will to Power (W. Kaufmann, Ed.; W. Kaufmann & R. J. Hollingdale, Trans.). Random House.
Nietzsche, F. (1990). Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future (R. J. Hollingdale, Trans.). Penguin Books.
Nietzsche, F. (2001). The Gay Science (B. Williams, Ed.; J. Nauckhoff & A. Del Caro, Trans.). Cambridge University Press.
Nietzsche, F. (2017). Nietzsche: On the Genealogy of Morality and Other Writings (K. Ansell-Pearson, Ed.; C. Diethe, Trans.; 3rd ed.). Cambridge University Press.
Reginster, B. (2006). The Affirmation of Life: Nietzsche on Overcoming Nihilism. Harvard University Press.
Schacht, R. (2023). Nietzsche’s Kind of Philosophy: Finding His Way. University of Chicago Press.
Solomon, R. C. (2004). Living with Nietzsche: What the Great “Immoralist” has to Teach Us. Oxford University Press.
Welshon, R. (2004). The Philosophy of Nietzsche. Acumen.
