Oleh: Syihabul Furqon
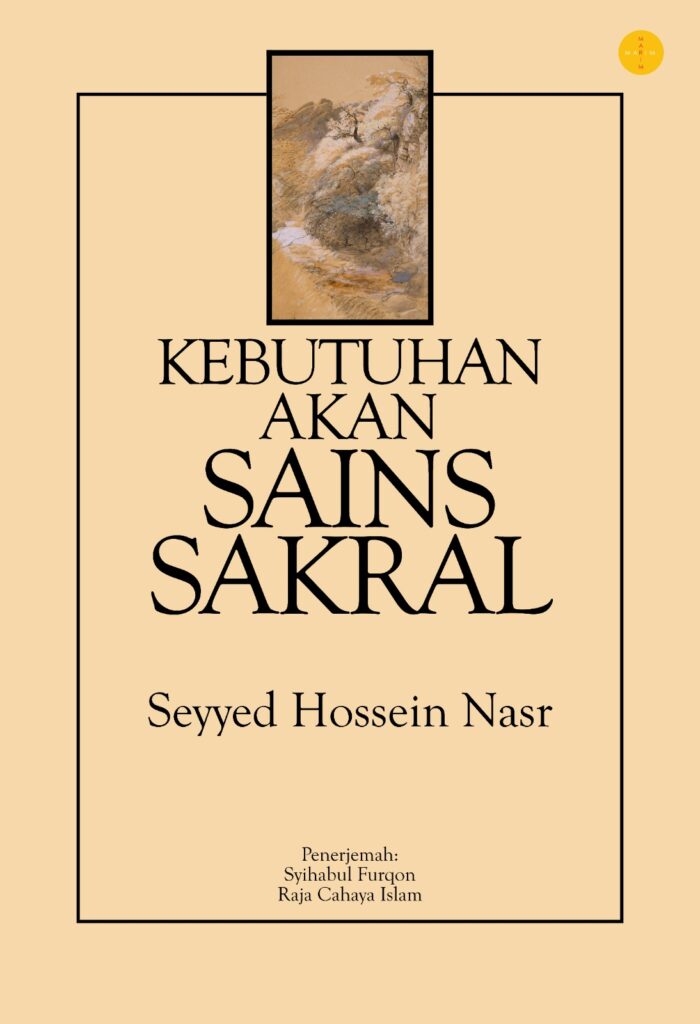
SAINS SAKRAL—Scientia Sacra—tak syak lagi merupakan perwakilan paling vokal saat ini dalam mengedepankan dimensi sapiensial manusia yang kompleks dan tak tepermanai. Dimensinya yang spontan, baik ekstremitas dan kelembutannya, terlalu naif bila direduksi ke dalam kategori oposisi biner dan kebenaran mata-kuda saintisme modern yang tunduk pada empirisme naif, positivisme naif dan absurditas demokrasi total dengan bentuk yang cenderung fasistik pada kebebasan yang dipilihnya sendiri.
Sebagai salah satu filsuf polymath lagi prolifik, Seyyed Hossein Nasr sampai abad 21 ini kukuh menyerukan tradisionalisme serta mengkritik habis apa yang disebutnya percepatan modern Barat yang gila-membangun (over develop) seraya tak mengindahkan krisis yang diakibatkannya sendiri. Ironinya adalah, di tengah krisis modern atas nama saintisme, temuan-temuan sains itu sendiri dinafikan. Ini tampak dari penyangkalannya pada krisis lingkungan yang kian akut, di samping kemerosotan moral dan etik atas manusia seraya mengkerdilkan dirinya sendiri sebagai tak lebih dari satu dari banyak partikel realitas. Tidak ada praktik lepas tangan dari krisis yang lebih naif selain yang dilakukan manusia modern.
Artinya dasar kesadaran manusia telah sedemikian rupa melenceng dari sains sebagai pengalaman, tidak sekadar objek dan realisme naif, melainkan sebagai satu kesatuan organik yang esensial dalam kehidupan manusia dengan seluruh sub strukturnya yang renik—bahkan metafisik. Tantangannya saat ini tidak hanya muncul dari berhala saintisme sendiri, melainkan dari implikasinya yang jauh berbahaya: krisis eksistensial. Krisis ini berakar dari tercerabutnya manusia dari hubungannya dengan Tuhan, atau sederhananya dari kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai manusia yang semata-mata dipikulnya. Di titik ini jenis fasisme ekologis apa pun, yang menihilkan manusia sebagai aktor dan subjek, entah atas nama realisme naif yang juga muncul dari dunia modern atau bahkan atas nama humanisme dan eksistensialisme Barat, yang lepas tangan pada soal-soal realitas sebagai yang integral, tak relevan. Sebab tak ada kebenaran universal tanpa kesadaran akan yang universal sebagai yang unitif sekaligus plural. Jatuhnya kesadaran pada satu titik saja senantiasa menggiring pada kecenderungan naif.
Dalam konteks abad 21, di mana pandemi Covid-19 menerjang seluruh dunia, semakin kentara kebutuhan akan sains sakral ini. Kemerosotan moral medis, informasi asimetris, dan upaya penggiringan pada kacamata-kuda saintisme modern yang nilainya (termasuk objektivitasnya) telah tereduksi ke dalam kepentingan politik dan ekonomi, menciptakan manusia yang ketergantungan pada kepastian yang semata-mata material. Sementara upaya-upaya penyadaran akan pentingnya kesadaran sapiensial, ketenangan, kesabaran, pendekatan integral, dan pada gilirannya kesadaran akan kefanaan, dinihilkan sebagai suatu kejumudan dan kekeraskepalaan. Bukankah tidak ada yang lebih keras kepala dari paksaan untuk menelan hanya satu informasi, sebagaimana menelan satu jenis obat dan pendekatan, serta kebenaran yang diulang-ulang oleh repertoar yang—siapa pun bahkan dirinya akan meragukan kebenaran itu, di suatu waktu dan saat tertentu?
Dalam satu kesempatan konverensi baru-baru ini, Seyyed Hossein Nasr, kurang lebih menekankan bahwa jika krisis kali ini (menyinggung dampak pandemi covid-19) menciptakan kekacauan dan betapa sulit mengendalikannya, padahal penemuan sains sedemikian pesat, menunjukkan kegagalan modernisme sendiri. Sebab bukankah tidak pernah ada yang disebut sebagai jaminan yang sebenar-benarnya—selain ilusi atas jaminan sendiri? Mungkin kekeliruan terbesar modern terletak pada sangkaannya bahwa dunia dapat ditundukkan, dan dengan itu datanglah ilusi akan jaminan semu tadi. Dalam tradisi Zen misalnya, jauh telah ditekankan bahwa pikiran yang beku adalah jalan yang salah. Pikiran beku ini dapat berarti berhentinya pikiran pada keadaan, atau simpulan tertentu, sehingga pola realitas yang spontan jadi mati—sebagaimana persis terjadi dalam modernisme—dan menggiring manusia pada ketidakluwesan tindakan, kekakuan kesimpulan. Sebuah kesalahan yang setara saat memutlakkan yang nisbi dan menisbikan yang mutlak dalam diskursus metafisika dan katakombe filsafat teoritik.
Atas dasar kebutuhan yang kian intens itulah kitab ini coba ditransmisikan ke dalam bahasa Indonesia. Bukan karena kurangnya kitab Nasr dalam bahasa kita yang telah diterjemahkan lebih dari sepuluh judul dan banyak lagi dalam fragmen serta volume ensiklopedi, melainkan karena pada karya inilah Nasr banyak mencurahkan konsentrasinya pada Sains Sakral serta implikasinya, tanpa mengesampingkan Knowledge and the Sacred yang telah lebih dulu diterjemahkan. Selain itu, studi atas pemikiran Nasr senantiasa relevan, bukan karena iklim intelektual Indonesia merupakan bagian dari peradaban Timur yang dalam pendahuluan Nasr di kitab ini masih mempraktikkan Sains Sakral dengan berbagai macam ragamnya, melainkan karena modernisme sedemikian rupa telah merenggut Tuhan dari kesadaran manusia secara umum, juga termasuk di Indonesia. Inilah juga yang dimaklumatka Muhammad Baqir dalam salah satu ceramahnya di Coll-300, 2019 silam. Selain itu, moga-moga kehadiran terjemahan ini, menyadarkan kita pada pendekatan yang holistik, metafisis sekaligus sapiensial sebagai upaya menghidupkan api dari jantung hikmah al-khalidah.
