Oleh: Rachmatullah Arken
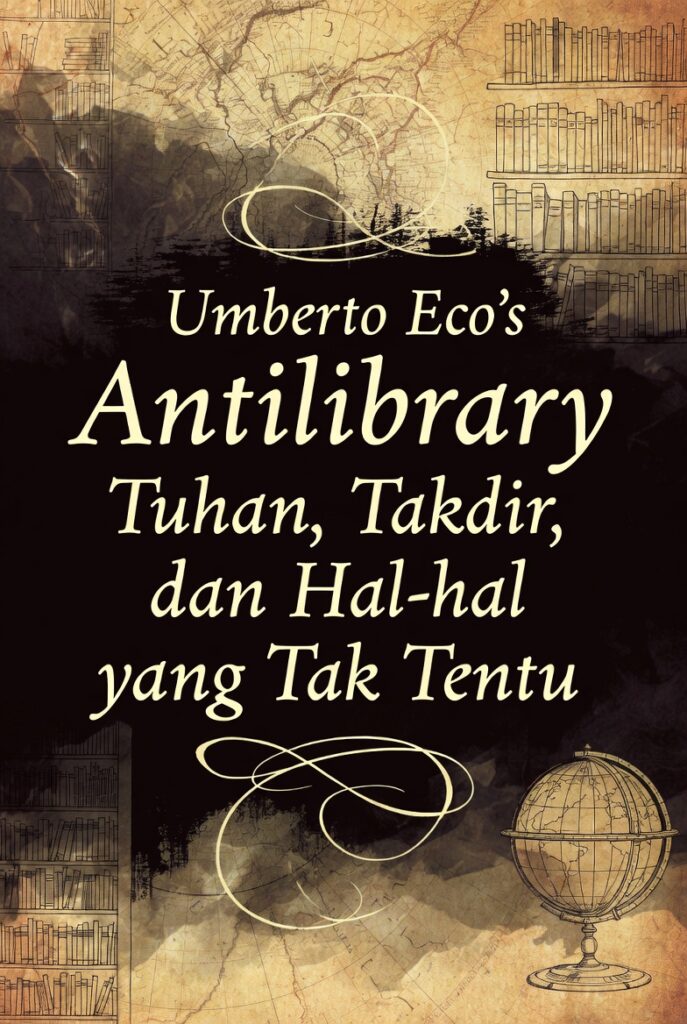
You will accumulate more knowledge and more books as you grow older, and the growing number of unread books on the shelves will look at you menacingly. Indeed, the more you know, the larger the rows of unread books. Let us call this collection of unread books an antilibrary. —Nassim N. Taleb
Umberto Eco’s antilibrary, demikian Nassim menulisnya. Frasa ini kubaca dari buku Nassim yang kubawa ke klinik saat dua orang pengunjung ruang Medika ini sedang riuh membicarakan masalahnya. Di bangku yang tak seberapa panjang, kami hadir seraya dalam hati menggerutu tentang AC yang tak kunjung menyala. Kupikir, ruangan ini hampir pasti sunyi jika saja kedua orang di hadapanku tidak hadir di sini. Tapi tentu tak akan kubiarkan ia menggangu Umberto Eco dan buku Nassim yang sedang singgah di pikiranku. Meski aku sebenarnya bisa saja beranjak ke halaman, tapi kuputuskan bertahan karena aku benci kekalahan. Lagipula, bukankah niatku kesini memang untuk mendapatkan pengobatan?
Umberto Eco’s antilibrary; frasa pendek tentang kondisi nalar saat bertatap dengan beribu lembaran buku yang luput dari waktu. Tak peduli berapa banyak naskah yang kita punya pada tumpukan buku itu, pikiran kita hanya bisa singgah pada apa yang tergeletak di atas meja. Yang terlihat dan sedang dibaca saja. Tapi itu lumrah memang, lagipula membeli dan mengoleksi buku tidak berarti selesai dikuasai dengan sendirinya, itu halu. Nah, persoalannya, ucap Nassim, beribu yang tak terbaca itu lebih menawarkan kemungkinan tentang ilmu, tentang peristiwa di masa depan yang tak tentu. Dan itu penting agar mengerti bahwa hidup bisa jadi tak seserius itu memang memerlukan pembacaan yang awas atas pelbagai kemungkinan itu.
Umberto Eco’s antilibrary; frasa ini sebenarnya memenuhi segala ketertarikanku tentang semesta dan keacakan. Jika saja kedua orang di hadapan ini bisa berhenti sebentar berbicara dan menikmati keheningan. Tentu karena keberadaan mereka bukan sejenis penyangkalan logis, bahwa waktu dan peristiwa di dalamnya tak pernah sepenuhnya aku kuasai. Dan peristiwa apapun punya peluang yang sama untuk berbagi dan menjadi. Aneh memang, sementara kewarasanku berharap jalinan takdir yang pasti, tapi dunia terlampau asyik menawarkan musykilnya hari. Dan itu akhirnya membuat Matematika lebih mirip dengan ramalan cuaca. Qadha dan Qadar seperti mantan yang terus menghindar. Sama-sama tak terduga. Tapi apakah seperti itu cara Tuhan bekerja?
Tuhan, Takdir Kreatif, dan Penderitaan
Dalam beberapa kesempatan aku sering bertanya: Jika skenario Tuhan itu pasti yang terbaik, apakah penderitaan manusia juga menjadi bagian darinya? Ataukah skenario Tuhan itu sebenarnya hanyalah ruang beribu kemungkinan layaknya halaman buku yang belum terbuka: hamparan aksaranya tercetak nyata, namun tafsir pikiran atasnya bisa berbeda ketika terbaca? Ataukah sebenarnya Tuhan hanya duduk di ‘Arsy-Nya seraya sesekali menyentil langkah manusia yang terlalu sibuk berlari di dunia? Membayangkan takdir yang kreatif itu memang sulit adanya. Semakin pikiran bekerja, semakin imaji imanku tertawa atas upaya bodoh memahaminya. Lalu aku ingat ungkapan Ibn ‘Arabi: “Al-‘ālamu kulluhu khayālun fī khayāl” (seluruh alam ini adalah khayal di dalam khayal). Ungkapan ini membuatku bingung sekaligus lega: bahkan jika hidup lebih banyak tragedi, maka itu bisa jadi hanyalah khayal acak dari ketidakmampuanku memahami takdir diri.
Masalahnya, hidup ini kadang terlalu acak. Ada hari-hari ketika pikiranku menyatakan manusia seharusnya diberi kebebasan yang nyata. Bukan sekadar ilusi ala Spinoza dalam ungkapan “determinatio negatio est”-nya. Detik ini pun rasanya aku bisa memilih apakah tetap duduk di ruang tunggu klinik ini atau berdiri dan kutinju saja muka dua orang yang berisik itu. Pilihan-pilihan kecil itu begitu menggelitik iman yang terus bertukar-tangkap dengan ragu. Tapi, bukankah madzhab kalam yang aku imani itu sudah jelas menjawabnya? Pikiranku tetiba mengingat para teolog Asy’ariyah itu. Ucap mereka, bayangkan saja manusia itu dititipkan kemampuan (qudrah) sementara. Dengan qudrah itu manusia bisa mengakuisisi (kasb) perbuatannya sendiri. Dus, orang tidak harus melihat dirinya sebagai penerima takdir yang buta. Meski semu, manusia sebenarnya sempat punya kuasa. Jika ia menderita, maka penderitaan itu adalah apa yang ia akuisisi dari pilihan terbaik Tuhan yang sudah menciptakannya.
Tapi aku sulit mengimani pendapat itu. Karena itu aku lebih menerima Tuhan yang dibayangkan Whitehead sebagai “the fellow-sufferer who understands” dan “the poet of the world, with tender patience leading it by his vision of truth, beauty, and goodness.” Tuhan adalah “sosok” sahabat yang menemani kita saat terluka. Tuhan adalah puisi semesta, dengan keindahan, kebaikan, dan kebenaran firman-Nya. Ah, ungkapan Whitehead ini pun masih sulit kupahami sebenarnya. Bayangan Tuhan yang begini seolah menggambarkan Dzat Segala Maha, namun dengan kekuasaan yang terbatasi oleh ketetapan-Nya sendiri. Tuhan seolah tidak punya kuasa untuk mengubah penderitaan, layaknya Thanos, cukup dengan menjentikkan jari. Tapi Whitehead menyadarkanku bahwaTuhan tidak pergi. Dia ada di sisi menemani. Dia memahami bahwa aku adalah makhluk-Nya yang seringkali hilang arti. Setidaknya, ketika merasa diri begitu jahat, aku tetap bisa membayangkan sosok-Nya yang bersahabat.
Barangkali itu pula yang dulu membuat Keith Ward harus menyangkal Dawkins, dan menyatakan bahwa penderitaan, konflik, kejahatan, keacakan, merupakan harga yang harus dibayar demi nilai-nilai intrinsik teleologis yang ada pada kehidupan. Nasib buruk, luka, derita, ataupun patah hati, merupakan kondisi niscaya dari tujuan kosmik, yang Tuhan memilih untuk tidak menghilangkannya. Namun, sekali lagi, Tuhan ada di sana menemani. Tapi mengingat manusia cenderung percaya hanya pada apa yang diinginkannya, pandangan Ward atau Whitehead itu bisa jadi terlalu mengada-ada. Bagaimanapun, tetap sulit membayangkan sosok Tuhan yang setia mendengarkan, namun tidak serta merta mengubah keadaan. Ada harapan tertentu dalam diri yang tetap bersuara: semestinya Tuhan bisa!
Hal-hal yang (masih) Tak Tentu
Bisa jadi pertanyaan yang benar bukan “apakah kita bebas atau ditentukan?”, tapi “mengapa Tuhan memilih cara yang paling acak untuk tetap dekat dengan kita?” Seperti Umberto Eco’s antilibrary, takdir hanya bermakna ketika pikiran ini menyadari ada lautan hikmah pada ribuan lembaran peristiwa yang sudah dijalani. Mungkin karena cinta-Nya yang terlalu besar, maka Tuhan tak pernah menjadikan takdir diri layaknya cerita yang sudah terbaca ujungnya sejak halaman pertama. Ia ingin menjadi antilibrary abadi: dengan lembaran yang tak habis terbaca. Setiap kali aku mengira sudah memahami isi lembaran, Ia akan mengingatkan bahwa masih banyak yang belum kubuka.
Lalu pikiranku mulai mereda seiring kebisingan yang kembali mengetuk telinga. Apa yang kusadari akhirnya adalah bahwa Umberto Eco’s antilibrary bukan cuma tentang buku-buku yang belum terbaca, melainkan juga tentang kasih Tuhan yang meski acak tapi begitu setia. Lalu takdir? Ia bisa jadi antilibrary terbesar yang pernah ada. Manusia boleh saja menghabiskan usia untuk memahaminya, tapi sisi lain peristiwa yang belum terbaca selalu menawarkan lebih banyak kemungkinan untuk makna. Barangkali antilibrary Eco bukan hanya tentang buku yang tak terbaca, tapi juga tentang ayat-ayat yang tersendat di telinga, nama-nama mantan yang sesekali datang meghardik lupa, atau takdir yang terus menuliskan ulang ceritanya. Barangkali itu juga yang membuat kita tetap datang pada-Nya, tetap bertanya, tetap berdoa.
Umberto Eco’s antilibrary; kini frasa ini tidak lagi mengejutkan pikiranku. Meski kubayangkan lautan buku, toh tak kan lantas terlihat juga nama yang kutunggu. Meski kuputuskan untuk beriman saja atas semua kebaikan, tetap saja sesekali pikiranku ragu. Seperti kedua orang di hadapanku yang kini justru lekat menatapku. Mungkin terpesona, atau barangkali curiga. Tapi itu cukup menjadi alasan untukku memilih beranjak begitu saja. Umberto Eco’s antilibrary: Aku kalah hari ini.
Bacaan:
Taleb, Nassim Nicholas. (2007). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House.
Ibn ‘Arabī. (tt.). Fuṣūṣ al-Ḥikam. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī.
Spinoza, Baruch. (1677). Ethica, ordine geometrico demonstrata. Parte I, Proposición 8, escolio.
Whitehead, Alfred North. (1978). Process and Reality: An Essay in Cosmology. New York: Free Press.
Ward, Keith. (2007). Divine Action: Examining God’s Role in an Open and Emergent Universe. West Conshohocken: Templeton Press.
